Kebangkitan Akhlak dan Kesadaran Nasional Berbasis Teknologi

HARI ini tepat 116 tahun yang lalu, sebuah bara pemantik mulai terpercik dan menimbulkan kilatan-kilatan cahaya yang menerangi jalan panjang menuju tervisualisasikannya cita-cita bangsa berbasis kesetaraan nilai-nilai adiluhung yang semestinya menjadi mimpi bersama ummat manusia.
Pendidikan dan akses terhadap pengetahuan menjadi kata kunci. Optimasi fungsi kognisi dengan sistematika belajar dan cara memilah serta memilih data yang layak untuk menjadi informasi serta dapat dikapitalisasi dalam proses prokreasi, menjadi prasyarat inti untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi.
Boedi Oetomo (BO) dan para tokoh cendekia pada jaman itu adalah reaktor sosial yang kemudian memfasilitasi proses akselerasi kebangkitan pemikiran tentang nasib bangsa dan melahirkan nasionalisme dari rahim pergulatan wacana berbagai komponen bangsa.
Sejarah mencatat ada sembilan orang yang disebut sebagai para tokoh pendiri BO, antara lain Soetomo, Soeradji Tirtonegoro, Goenawan Mangoenkoesoemo, Mohammad Soelaiman, Gondo Soewarno, Raden Ongko Prodjosoedirdjo, Mochammad Saleh, dan Raden Mas Goembrek.
Dalam perjalanannya, banyak tokoh nasional yang bergabung dengan BO, seperti Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara), Tjipto Mangoenkoesomo, Tirto Adhi Soerjo, Pangeran Noto Dirodjo, Raden Adipati Tirtokoesoemo, dan kawan-kawan.
Para pendiri awal BO berasal dari sekolah dokter STOVIA (School Tot Opleiding Van Idlandche Artsen), yang antara lain dapat diakses oleh para calon dokter pribumi karena adanya penerapan kebijakan politik etis dari pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Menyitir Sartono Kartodirdjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional (2014: 38), salah satu tokoh penggagas politik etis atau kebijakan balas budi Belanda adalah Conrad Theodor (C.Th.) van Deventer.
Perkembangan global saat itu yang mulai mengkritisi kebijakan kolonisasi dan penjajahan serta diskriminasi, termasuk perbudakan bermuara pada lahirnya gerakan-gerakan pro humanisme global yang mendesak adanya perubahan perlakuan pada warga koloni, yang sejatinya tentulah sesama manusia juga.
Berawal dari penerapan politik etis di awal abad ke-20 itulah, pendidikan menjadi salah satu lentera yang menerangi jalan setapak kebangsaan menuju pelataran kemerdekaan yang semestinya memang merupakan hak setiap bangsa dan anak manusia di dalamnya.
Tak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks pencerahan umat manusia, pendidikan dan filsafatnya memiliki peran krusial dalam mengarahkan perkembangan intelektual dan moral individu, serta dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan beradab.
Mari sejenak kita simak teori-teori dalam filsafat pendidikan yang mungkin terkait dengan proses kebangkitan nasional yang terpantik karena terjadinya pencerahan kognisi anak bangsa.
Perennialisme, teori ini berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mengajarkan prinsip-prinsip universal dan abadi yang dapat ditemukan dalam karya-karya besar peradaban manusia. Tokoh utama dari teori ini adalah Robert Hutchins dan Mortimer Adler, yang menekankan pentingnya pendidikan liberal yang menekankan pada pemikiran kritis dan dialog Socratic.
Esensialisme, teori ini berbeda dengan perennialisme, esensialisme berfokus pada pendidikan yang berpusat pada penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan, keterampilan dasar, dan pembentukan karakter. William C. Bagley adalah salah satu tokoh utama dari teori ini. Esensialisme menekankan pentingnya disiplin, otoritas guru, dan kurikulum yang kuat dan ketat.
Progresivisme, dimana teori yang satu ini dipelopori oleh John Dewey yang berpendapat bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan pengalaman langsung. Progresivisme menekankan pembelajaran yang aktif dan berbasis proyek, di mana siswa belajar melalui pengalaman dan penemuan sendiri.
Lalu ada rekonstruksionisme dari George S. Counts dan Theodore Brameld, yang melihat pendidikan sebagai alat untuk merekonstruksi masyarakat menuju keadilan sosial. Rekonstruksionisme menekankan peran pendidikan dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan mempromosikan perubahan sosial.
Sedangkan dalam konteks kebangkitan masyarakat secara multidimensi, tentu kita mengenal konsep dan pemikiran Paulo Freire bukan?
Freire, seorang filsuf pendidikan dari Brazil, dikenal dengan karyanya Pedagogy of the Oppressed, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan individu dari penindasan dan ketidakadilan sosial.
Politik Etis yang diterapkan di wilayah koloni Hindia Belanda memungkinkan perluasan kesempatan pendidikan menengah bagi penduduk asli Indonesia.
Pada tahun 1925, fokus pemerintah kolonial bergeser ke penyediaan pendidikan kejuruan dasar selama tiga tahun.
Pada tahun 1940, lebih dari 2 juta siswa telah bersekolah sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 6,3 persen yang tercatat dalam sensus tahun 1930.
Pada tahun 1940, antara 65.000 hingga 80.000 siswa Indonesia bersekolah di sekolah dasar Belanda atau sekolah dasar yang didukung Belanda, atau setara dengan 1 persen dari kelompok usia yang sesuai.
Sementara di sekitar waktu yang sama, ada 7.000 siswa Indonesia belajar di sekolah menengah menengah Belanda. Sebagian besar siswa sekolah menengah bersekolah di MULO.
Meskipun jumlah siswa yang terdaftar relatif sedikit dibandingkan dengan total kelompok usia sekolah, pendidikan menengah Belanda memiliki kualitas yang baik dan sejak tahun 1920-an mulai menghasilkan elit Indonesia terdidik.
Lahirlah suatu kelompok masyarakat elit yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berpikir kritis dan konstruktif serta memiliki perspektif yang lebih luas dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan. Termasuk dalam menilai kondisi bangsa dan keputusan-keputusan untuk memperjuangkan nasib bangsa dalam kerangka idealisme untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusian yang bersifat universal dan egaliter.
Dari fase pemantik BO lah lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dengan berbagai dinamika dan pergulatan di dalamnya sebagai bentuk pencarian kesetimbangan atau homeostasis dari reaksi persenyawaan berbagai unsur dan elemen bangsa yang dikatalisa pengetahuan tentang harkat dan martabat manusia.
Reaksi tersebut dalam ranah kimia dapat dihitung secara kuantitatif reaktan dan produknya dengan pendekatan stoikiometri. Sementara dalam reaktor kebangsaan, gejolak dan dinamika yang terjadi mungkin saja merupakan bagian tak terpisahkan dari proses termodinamika yang dapat mengkonversi energi pergolakan menjadi energi turbo untuk pencapaian terjadinya akselerasi penyelarasan yang berkesinambungan.
Energi kebangkitan nasional pulalah yang telah membawa kita secara kinetika memasuki ruang waktu abad ke 21, dimana revolusi tengah terjadi yang ditandai dengan bangkitnya the reign of technology.
Seorang Elon Musk yang menguasai jaringan internet berbasis koloni satelit low earth orbital, chip otak Neuralink, dan teknologi catudaya listrik di sektor transportasi, bersama Sam Altman yang membesut Chat GPT melalui Open AI dan Yann LeCun yang membidani lahirnya CNN (convolutional neural network) serta proyek FAIR-nya Facebook dari Meta milik Zuckerberg, serta peneliti bioteknologi seperti Dodna dan He Jiankui, kini tengah memantik proses kebangkitan Homo Sapiens, yang mungkin akan bertransformasi menjadi makhluk hibrida baru dalam proses evolusi adaptif yang menikahkannya sendiri dengan produk teknologi yang dikembangkannya sendiri pula.
Di sisi lain, akumulasi ekses yang terlahir dari proses hiperkompetisi yang mereduksi sifat empati dan peduli telah terbukti banyak mengerosi konstruksi akhlak yang fondasinya dibangun dengan struktur etika dan norma yang dilahirkan untuk mengakomodir kepentingan bersama.
Egosentrisme telah melahirkan pragmatisme yang memicu sikap hedonik dan pengabaian terhadap etik dan nilai kebaikan yang bersifat fundamental. Korupsi, perusakan lingkungan berdalih pemenuhan kebutuhan, kekerasan di ruang publik, serta berbagai kondisi patologi sosial lainnya kian menggejala dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika peradaban yang terus melahirkan perubahan demi perubahan.
Apakah pendidikan dan keterbukaan akses pengetahuan saat ini, dapat kembali menjadi pemantik perubahan peradaban sebagaimana akses pendidikan telah melahirkan gerakan seperti Boedi Oetomo dan berbagai inisiatif kemerdekaan pada jamannya? Bukankah masa Renaissance pun demikian? Ditandai dengan tumbuhnya kesadaran yang dilahirkan oleh proses dan mekanisme berpikir kritis, sistematis, dan konstruktivis, terkondisikanlah suatu era dimana nilai kemanusiaan mendapat energi untuk mengentaskan berbagai persoalan yang berkelindan dengan kejumudan, kenaifan, dan kerakusan instingtual.
Apakah pendidikan masih memiliki peran krusial sebagaimana era politik etis diterapkan di Hindia Belanda? Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat pendidikan mayoritas penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas telah mencapai wajib belajar 9 tahun atau tamatan SMP/sederajat ke atas.
Tamatan pendidikan terbanyak berasal dari SMA/sederajat dengan persentase 30,22 persen pada Maret 2023. Kedua terbanyak adalah lulusan SD/sederajat, dengan capaian 24,62 persen. Disusul oleh jenjang sekolah SMP/sederajat sebanyak 22,74 persen.
Sementara perguruan tinggi proporsinya hanya 10,15 persen pada Maret 2023. Di samping itu, persentase yang tidak tamat SD/sederajat dan belum pernah sekolah cukup tinggi, masing-masing sebesar 9,01 persen dan 3,25 persen.
Sementara mengutip data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,23 juta per Juni 2021, yang jika diperinci berdasarkan jenjang pendidikan hanya sebanyak 59.197 ribu jiwa atau 0,02 persen yang berpendidikan hingga strata S3.
Kemudian, sebanyak 822.471 ribu jiwa atau 0,03 persen penduduk yang berpendidikan hingga jenjang S2. Lalu, penduduk yang berpendidikan hingga S1 sebanyak 11,58 juta (4,25 persen), jenjang D3 sebanyak 3,46 juta jiwa (1,27 persen), serta D1 dan D2 mencapai 1,15 juta jiwa (0,42 persen). Total hanya sebanyak 17,08 juta jiwa (16,7 persen) penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Tetapi tak dapat dipungkiri, teknologi informasi dengan berbagai fasilitas yang ditawarkannya, tak pelak adalah bagian dari ekstensi kapasitas manusia yang selama ini terbatas pada fungsi kognisi otak, sistem inderawi, dan kapasitas psikomotoriknya.
Media sosial telah bertransformasi menjadi media komunikasi yang mampu mereduksi keterbatasan akses dan hendaya waktu serta limitasi jumlah koneksi. Relasi tak lagi terbatasi transmisi, dan informasi telah menjadi produk wajib atau mandatori.
Pada Januari 2023 saja tercatat oleh datareportal.com bahwa Indonesia memiliki 167 juta pengguna aktif media sosial, yang setara dengan 60,4 persen dari total populasi. Sementara, We Are Social dan Meltwater melaporkan bahwa pada Januari 2023, Indonesia memiliki 212,9 juta pengguna media sosial.
Dalam State of Mobile 2024 yang dirilis oleh Data.AI warga Indonesia menjadi pengguna yang paling lama menghabiskan waktu dengan perangkat mobile seperti telepon genggam dan tablet pada 2023, yaitu 6,05 jam setiap hari. Sementara tercatat pada tahun 2023 pula, bahwa 67,29 persen warga Indonesia menggunakan telepon genggam. Sungguh suatu proporsi yang cukup istimewa bukan?
Artinya penetrasi teknologi dan tingkat ketergantungannya telah memiliki rasio cukup tinggi terhadap proporsi populasi anak negeri. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagi kita semua, kemana arah transformasi akan kita navigasi? Vektorisasi energi yang lahir dari reaksi dan dinamika potensi semestinya menjadi bagian dari strategi dari konsep kewaskitaan negeri.
Kajian dan berbagai proyeksi telah menjadi bukti, bahwa domain kompetisi karena keterbatasan sumber daya berbasis alam, dapat bergeser menjadi model-model kolaborasi dan kooperasi dengan semangat saling mensubstitusi, mengomplementasi, dan mengaugmentasi dengan berbasis pada platform teknologi, untuk mengembangkan teknologi, dan menjadikan teknologi sebagai enzim pengkatalisa berbagai reaksi terkait dinamika yang dilahirkan oleh berbagai model baru proses relasi.
Augmentasi kapasitas kognisi dengan fasilitasi AI (LLM, ASI, dll) akan menggeser limit kapasitas prokreasi dan dapat diprediksi akan melahirkan begitu banyak inovasi.
Konsep dan mekanisme pendidikan dan diseminasi pengetahuan akan mengalami transisi, demikian juga model bisnis dan relasi sosial akan memasuki model-model baru yang bahkan saat ini belum kita kenal.
Kecepatan, ketepatan atau akurasi, daya antisipasi atau prediksi, strategi yang presisi, dan inovasi yang teroptimasi akan menjadi ciri.
Lihat saja solusi transportasi urban dengan ART (Autonomous Rail Rapid Transit) berpemandu LIDAR yang didukung IoT dan AI. Tak perlu jalan atau rel khusus, bercatudaya ramah lingkungan dan berkesinambungan (listrik atau hidrogen), bersistem cerdas terotomasi, dan tentu saja tak memerlukan biaya tinggi untuk investasi di aspek konstruksi, adalah contoh inovasi yang dapat dilahirkan oleh analisis data jeli yang dibantu AI.
Demikian juga penemuan dan pengembangan obat-obat kedokteran presisi yang dapat diakselerasi oleh pendekatan in silico berbasis data molekul, termasuk strukturnya, data penyakit, genom dll yang semua dapat dianalisis dan dicarikan aspek asosiasi serta korelasi nya oleh sistem cerdas berbasis AI.
Maka tak pelak kita semua perlu merenungkan kembali. Apakah esensi dari kebangkitan yang dapat kita pantik hari ini?
Kebangkitan akhlak dan kesadaran menurut saya adalah esensi. Saya telah lelah dan jengah dengan pragmatisme dan hedonisme dalam konteks dekonstruktif yang hari ini menggejala di seantero negeri. Korupsi, buang sampah seenaknya, mencontek, plagiasi, suap-menyuap dan pungli, premanisme dan penyalahgunaan kekuasaan, fitnah dan saling menyakiti, tak menghargai hak dan kepemilikan orang lain, sopan santun dan adab dalam berperilaku dan berbahasa, serta berbagai gejala lainnya yang merepresentasikan menipisnya fondasi nilai moral telah menjadi pengingat secara faktual.
Dan teknologi sebenarnya dapat menjadi "politik etis" kedua, dimana politik etis pertama telah melahirkan Boedi Oetomo, maka semestinya teknologi dapat melahirkan komunitas dengan semangat yang sama, dan menjadi pemantik kebangkitan akhlak dan kesadaran bangsa melalui pemerataan akses informasi dan edukasi, peluang berinovasi, dan terciptanya tata kelola dengan nilai transparansi dan objektivitas tinggi.
Sistem seperti social credit system yang memantau dinamika interaksi kemasyarakatan di ruang publik dapat diadopsi dengan berbagai moderasi pada berbagai fungsi tentunya. Demikian pula akuntabilitas dan objektivitas pada pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan akusisi sistem berteknologi.
Efisiensi akan terjadi, demikian pula optimasi konsumsi energi yang berdampak pada kebersinambungan keselarasan lingkungan akan dapat dicapai.
Berbagai proses yang digawangi oleh sistem cerdas terotomasi akan mengurangi potensi manipulasi dalam berbagai bentuk relasi yang berkonotasi transaksi.
Besar harapan hidup kita ke depan akan lebih harmoni, terorkestrasi antara kearifan kemanusiaan dan kecanggihan teknologi. Kesetimbangan baru akan terjadi, dan kebangkitan yang dinanti akan maujud dalam sebentuk pencapaian manusia yang lebih berorientasi pada proses pengenalan dan pengembangan diri dalam kapasitasnya sebagai makhluk multidimensi.
Penulis: Tauhid Nur Azhar
Ahli neurosains dan aplikasi teknologi kecerdasan artifisial, SCCIC ITB/TFRIC-19.


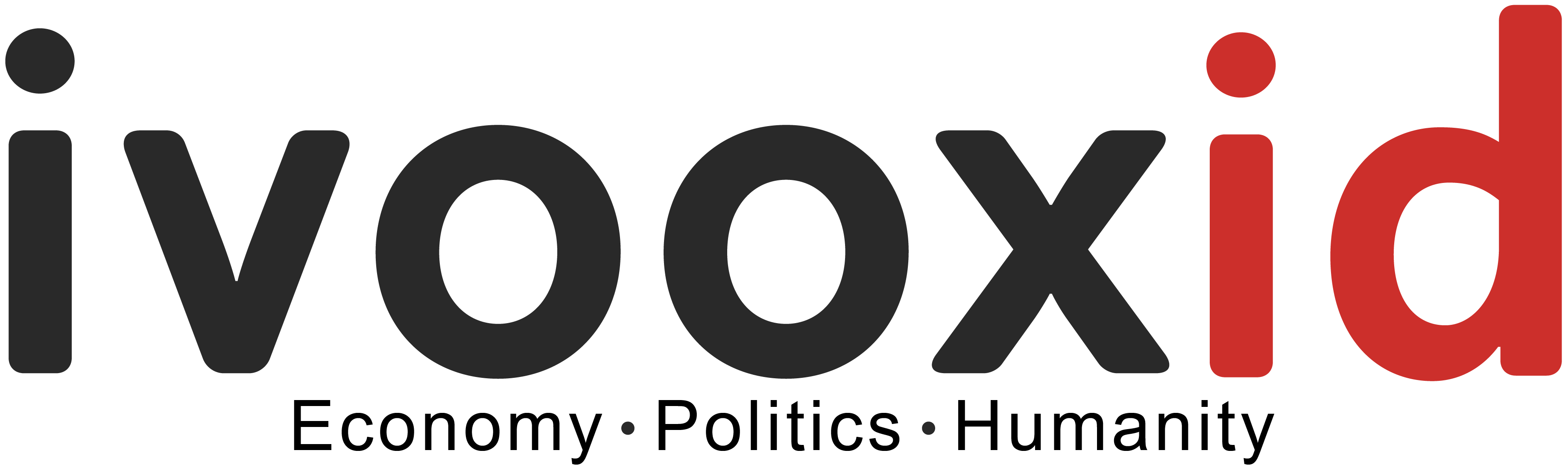
0 comments